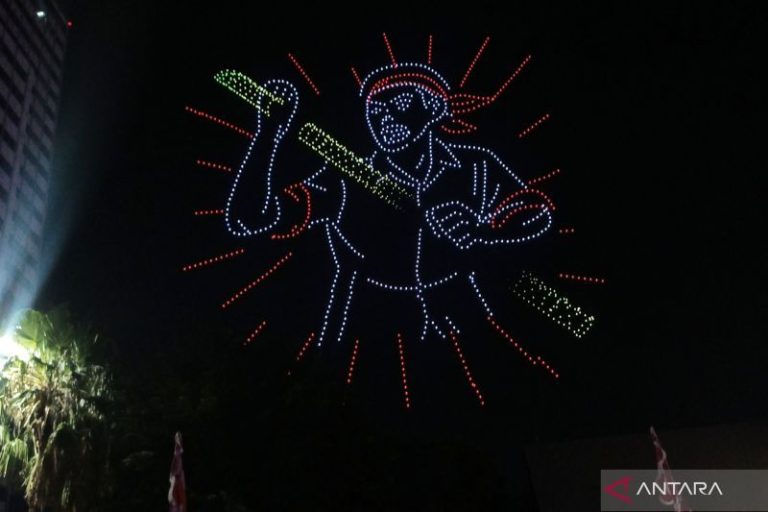JAKARTA, (ANTARA) – Delapan dekade sudah Indonesia merdeka, dan perjalanan panjang dalam membangun ekonomi negeri pun telah dilalui. Indonesia yang yang lahir di tengah keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia terdidik, kini bertransformasi menuju salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia.
Perjalanan panjang ini bukan hanya kisah pembangunan fisik, tetapi juga transformasi struktur ekonomi, kebijakan strategis, dan daya juang masyarakat yang membentuk fondasi menuju cita-cita besar: Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan data dari World Bank, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang pada tahun 1967 hanya sekitar 7,7 miliar dolar AS, telah melampaui 1,5 triliun dolar AS pada 2024. Tingkat kemiskinan yang pada awal kemerdekaan diperkirakan di atas 70 persen populasi, turun menjadi sekitar 9,36 persen per Maret 2024 (BPS).
Perjalanan ini menunjukkan transformasi besar dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah, meski tantangan middle income trap masih membayangi.
Untuk itu tahun 2025 menjadi momentum refleksi nasional yang penting: delapan dekade perjalanan Indonesia merdeka. Perjalanan panjang ini bukan hanya kisah politik dan sosial, tetapi juga perjalanan ekonomi yang berliku, penuh tantangan, tetapi sarat capaian.
Selama 80 tahun Indonesia telah melewati fase-fase krusial, dari perekonomian yang porak-poranda akibat perang, menuju tahap pembangunan, krisis, reformasi, hingga era digital dan hilirisasi sumber daya alam.
Era Pembangunan Ekonomi
Era fondasi ekonomi (1945–1965) merupakan masa awal kemerdekaan yang diwarnai oleh instabilitas politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia saat itu masih berbasis agraris, dengan infrastruktur terbatas dan inflasi yang sangat tinggi.
Pada 1965, inflasi bahkan mencapai 650 persen (BPS), akibat dari defisit fiskal besar, pembiayaan melalui pencetakan uang, dan situasi politik yang memanas. Pemerintah pada saat itu fokus pada pembangunan fondasi ekonomi yang terdiri dari nasionalisasi aset-aset Belanda pada awal 1950-an, pembentukan bank sentral (Bank Indonesia pada 1953), dan perencanaan pembangunan lima tahun pertama.
Namun, keterbatasan kapasitas fiskal dan lemahnya basis industri membuat pembangunan berjalan lambat. Meski demikian, pada periode ini lahir kesadaran bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian integral dari kedaulatan nasional.
Setelah itu dilanjutkan era Pembangunan Orde Baru (1966–1998) di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto, dengan memprioritaskan stabilisasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Langkah awalnya adalah mengendalikan inflasi, yang berhasil ditekan dari 650 persen pada 1965 menjadi di bawah 20 persen pada awal 1970-an.
Era Reformasi
Berikutnya era reformasi yang membawa perubahan fundamental dalam tata kelola ekonomi: desentralisasi fiskal, reformasi perbankan, dan pembentukan lembaga-lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Krisis 1998 mendorong Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam mengelola defisit anggaran dan utang publik. Kebijakan disiplin fiskal melalui UU Keuangan Negara membatasi defisit maksimal 3 persen dari PDB dan rasio utang maksimal 60 persen dari PDB.
Pada dekade 2000-an, harga komoditas dunia yang tinggi memberikan angin segar bagi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5–6 persen per tahun, inflasi relatif terkendali, cadangan devisa meningkat signifikan, dan menurut Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan turun dari 24 persen pada 1998 menjadi 11,25 persen pada 2014.
Membangun Manusia dan Inovasi
Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tak lepas dari pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 74,39 pada tahun 2023.
Namun, kondisi tersebut masih tertinggal dibanding negara-negara OECD. Jepang, misalnya, mencatat IPM sebesar 90,1 pada tahun 2023, sementara Korea Selatan berada di angka 92,2 dan Australia di 93,0. Lebih jauh lagi, laju kenaikan IPM di negara-negara tersebut tetap konsisten meskipun mereka sudah berada di kategori sangat tinggi, yang menunjukkan adanya fokus berkelanjutan pada peningkatan kualitas manusia, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, dan untuk itu investasi pada pendidikan vokasi, riset teknologi, dan literasi digital harus ditingkatkan.
Selanjutnya pembangunan ekonomi berbasis inovasi juga menjadi kunci. Potensi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030 (Google-Temasek-Bain, 2023). Hilirisasi sumber daya alam harus beriringan dengan penciptaan ekosistem startup teknologi, bioteknologi, dan industri kreatif yang mampu mengekspor produk bernilai tambah tinggi.
Tantangan dan Peluang Menuju 2045
Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, melainkan target konkret untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dengan PDB di atas 9 triliun dolar AS dan PDB per kapita sekitar 25.000 dolar AS.
Untuk itu, ada dua jalur besar yang harus ditempuh, yakni penguatan ekonomi makro dan optimalisasi ekonomi mikro. Dari sisi makro, stabilitas fiskal dan moneter menjadi harga mati. Defisit APBN harus dijaga di bawah 3% PDB dengan fokus pada pembiayaan produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan riset teknologi.
Transformasi energi menuju sumber terbarukan perlu dipercepat untuk mengurangi ketergantungan pada fosil dan menjaga daya saing jangka panjang. Sementara dari sisi mikro, penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi harus diprioritaskan. Data Kemenkop UKM menunjukkan UMKM menyumbang lebih dari 60,5% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja.
Sehingga melalui berbagai upaya digitalisasi usaha, akses pembiayaan murah, serta peningkatan kualitas SDM, semua itu akan menjadi katalis agar UMKM Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas ke pasar global.
Sejumlah peluang besar juga terbentang menjelang 100 tahun Indonesia merdeka,. Bonus demografi dengan 70% penduduk berada pada usia produktif hingga 2035 memberikan potensi pertumbuhan tinggi. Syaratnya, investasi pada pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja harus menjadi prioritas.
Tantangan lain adalah transisi menuju ekonomi hijau. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan lebih dari 400 GW, tetapi pemanfaatannya masih di bawah 2%. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon bukan hanya komitmen iklim, tetapi juga peluang menciptakan jutaan lapangan kerja baru.
*) Dr. M. Lucky Akbar adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Kementerian Keuangan.
(Oleh: Lucky Akbar | Editor : Dadan Ramdani)